“Sudah tiba,”
Aku menatap ke
arah gedung apartemen Tiffany. Gedung setinggi dua puluh lima lantai itu nampak
menjulang tinggi, menerangi langit hitam dengan cahaya lampu di setiap
lantainya.
“Akhirnya tiba
juga. Perjalanan pulang tadi terasa lama,” ujarku.
“Ya, begitulah.
Dan kau... Apa kau ingin menginap? Sudah malam, dan aku takut kau malah tak
bisa masuk ke rumah,” tawar Tiffany.
“Tidak, terima
kasih. Kau harus beristirahat. Jika aku menginap di tempatmu, kau takkan bisa
tidur karena aku akan mendengkur,”
“Ah, kau takkan
mendengkur. Kau kan masih polos,”
“Ah, lagi-lagi kau
menyebutku polos. Hmm... Baiklah, kurasa kau lebih baik segera naik ke
apartemenmu. Di luar dingin dan kau bisa sakit,”
“Lalu kau
sendiri?”
“Aku akan berjalan
sampai stasiun MRT,”
“Apa kau yakin?
Atau, bagaimana kalau kau naik taksi saja?”
“Entahlah. Lihat
saja nanti,”
“Tapi entah kenapa
aku khawatir denganmu. Sudahlah, kau menginap saja semalam,”
“Tak perlu. Aku
hanya akan merepotkanmu,”
“Tentu saja tidak!
Kau kan akan sudah bersedia membantuku untuk mengurus tempat konser anak-anak.
Lantas, kenapa aku tak bisa membantumu?”
“Tapi aku memang
tak bisa. Aku harus bekerja besok. Lagipula, kasihan adikku pasti menunggu di
rumah,”
Tiffany menghela
nafas panjang. Ia lalu menggosok-gosokkan kedua tangannya.
“Sudah, kau lebih
baik masuk ke apartemenmu sekarang. Kau pasti kedinginan,” ujarku.
“Kurasa begitu.
Baiklah kalau kau memang harus pulang. Hati-hati di jalan, Lee. Kalau ada
apa-apa beritahu aku, dan...”
“Dan apa?”
“Terima kasih
untuk malam ini,”
Aku tersenyum
padanya. Tiffany lalu berbalik dan pergi masuk ke gedung apartemennya. Aku
mengawasinya sampai ia benar-benar masuk ke dalam lift. Setelah yakin bahwa ia
akan aman, aku pun bergegas pulang. Ah, stasiun MRT terdekat dari sini jaraknya
cukup jauh. Aku harus berlari nampaknya agar bisa sampai lebih cepat.
“Malam ini dingin
juga rupanya,” gumamku.
Aku berjalan di
trotoar sambil mencoba menghibur diriku sendiri yang kedinginan. Ya, aneh
sekali malam ini begitu dingin. Padahal biasanya, malam-malam di Singapura
terasa panas. Atau setidaknya, malam-malam tak pernah sedingin ini. Sedang
berusaha menembus dinginnya malam, aku mendengar suara berderu dari arah
belakang. Tumben sekali ada truk atau bus yang lewat ke jalan ini. Biasanya,
hanya mobil-mobil pribadi yang melalui jalan ini. Maklum saja, ini area
perumahan dan sebenarnya memang mobil-mobil besar, bus, atau truk tak bisa
menggunakan jalan ini dengan bebas. Semakin lama suara menderu itu semakin
nyaring terdengar, dan yang membuatku terkejut adalah ketika kudengar suara
klakson yang cukup nyaring. Aku berbalik dan beberapa orang menghentikan
motornya di sampingku. Ada beberapa orang dengan pakaian serba hitam menghampiriku.
Beberapa dari mereka membawa tongkat pemukul baseball dan botol bir. Di antara
orang-orang itu, ada dua orang yang kukenal. Kevin, sahabatku sejak sekolah
dasar dan... Mike, lagi?
“Kau butuh
tumpangan?” tawar Mike.
“Mau apa lagi
kau?” tanyaku kesal.
“Aku hanya
menawarimu tumpangan. Toh sedari tadi kau pergi dengan kendaraan umum saja.
Pasti kau tak punya uang untuk membeli motor atau mobil,”
“Memang apa
urusanmu?”
“Huh, anak bodoh..
Kalau kau ingin berpacaran, lebih baik punya kendaraan. Ayolah, jangan
membuatmu tampak konyol di depan Tiffany,”
“Kau mengikutiku
dari tadi?!”
Mike langsung
menghampiriku dan mencengkram leherku kuat. Ia lalu mendorongku ke pagar dan
mengangkatku cukup tinggi sehingga membuatku tak bisa bernafas.
“Le, lepaskan!” aku
meronta.
“Mau sampai kapan
kau kabur seperti ini, hah?! Kau lupa bahwa kau masih ada urusan dengan kami?” tanya
Mike sinis.
“Urusan apa lagi?!
Kalian sudah cukup membuat hidupku dan hidup teman-temanku hancur! Mau apa
lagi?!”
“Kau pikir pengkhianatan
bisa dimaafkan semudah itu, hah?! Jangan bodoh! Kau tak lihat apa yang
anak-anak ini bawa?”
“Aku tak takut!”
“Cih, dasar
gelandangan! Anak-anak, habisi saja dia!”
Mike melemparku ke
trotoar, dan belum siap aku dengan kuda-kudaku, orang-orang itu sudah
menyerangku. Kontan saja aku sulit menyerang balik. Satu orang melawan empat
orang. Tangan kosong melawan tangan bersenjata. Bagaimana aku bisa menang? Aku
lantas lebih banyak melindungi diriku sendiri, menangkis serangan mereka semampuku.
Perut, dada, betis, dan kepalaku jadi sasaran mereka. Jemariku terasa sangat
sakit karena terkena hantaman tongkat baseball ketika aku melindungi bagian
belakang kepalaku. Aku mencoba menendang beberapa dari mereka di bagian perut
dan dada. Dalam keadaan seperti ini, kemampuan Taekwondo-ku memang harus
kugunakan. Tapi sehebat apapun kemampuan Taekwondo-ku, jika diserang oleh
banyak orang seperti ini tetap saja aku kalah. Aku pun semakin melemah,
sementara mereka terus saja membabi buta. Klimaksnya, kepala dan punggungku
terkena hantaman tongkat baseball dan aku langsung terkapar. Sambil menahan
sakit, aku berusaha untuk bangkit, tapi tak bisa. Mike menghampiriku dan
memijakkan kakinya di kepalaku.
“Kuberi kau dua
pilihan, kembali bersama kami atau kau akan terus mengalami mimpi buruk semacam
ini,” ujarnya.
“Aku... Aku
tak...”
“Jawab sekarang!!”
Mike malah
menjejakkan kakinya lebih keras. Aku mengerang kesakitan.
“Jawab sekarang!”
“Aku... aku tak
mau bergabung bersama kalian lagi!”
Mike mengangkat
kakinya dari kepalaku, dan menendang punggungku. Aku sudah tak mampu untuk
berteriak meminta tolong. Hanya eranganku yang terdengar oleh orang-orang di
sekitarku saja.
“Lee, bahkan
sahabatmu sendiri tak ingin sepertimu! Sahabatmu tak ingin menjadi pengkhianat!
Ia memilih tetap bersama kami daripada harus menjadi pengkhianat sepertimu!”
bentak Mike.
“Kalian yang
menghasut Kevin!” tepisku.
Dengan pandangan
yang buram, kutatap Kevin. Kevin hanya bisa menatapku dalam bisu. Ia melihatku
dengan tatapan dingin.
“Kevin, kau tahu
kita bersahabat sejak dulu. Aku percaya padamu. Mereka pasti menghasutmu!” ujarku.
“Kau yang
berkhianat,” ujar Kevin dingin.
“Apa?”
“Kau yang
berkhianat. Aku tahu itu,”
Aku terkejut
mendengar ucapan Kevin. Kenapa, kenapa ia, sahabatku tak menolongku? Bahkan
ketika aku dipukuli pun ia hanya menonton saja, melihatku babak belur dan
terkapar bersimbah darah.
“Nah, kau dengar
itu, Lee? Sahabatmu sudah tak mau lagi percaya padamu!” Mike memanas-manasi
keadaan.
“Aku tak peduli!
Kevin, kita masih bersahabat, ‘kan? Kau ingat ketika kita masih bersekolah
dulu, kau selalu memintaku menolongmu mengajari matematika. Kau akan marah jika
aku tak menemanimu. Ketika aku tak sengaja meninggalkanmu di kelas musik, kau
menangis. Sepulang sekolah, kita biasa bermain basket, dan di akhir pekan kita
akan pergi ke gereja bersama-sama,” kenangku.
“Dia sudah tak
butuh kenangan seperti itu!”
“Kevin! Kumohon!
Jangan seperti ini! Jangan kecewakan orang-orang di sekitarmu. Ibumu pasti akan
sedih jika tahu kau...”
“Jangan pernah
ikut campur urusan keluargaku!”
Aku terkejut
ketika Kevin membentakku seperti itu. Kevin nampak marah. Begitu kecewa aku
menyadari bahwa sahabatku sudah tak lagi seperti dulu. Air mataku mengalir
karena kekecewaan yang Kevin buat.
“Kukira kita masih
bersahabat...” ujarku pelan.
“Hentikan ucapanmu
itu!” potong Kevin tegas.
“Hmm... Kurasa
lebih baik kita segera pergi dari sini. Semakin lama, keadaannya semakin
mengesalkan. Ah, persahabatan... Busuk! Dalam persahabatan seharusnya tak ada pengkhianatan!
Tapi sebelum pergi, apa kau ingin memberikan hadiah terakhir untuk sahabatmu,
Kevin?” ujar Mike dengan nada merendahkan.
Kevin menghampiriku.
Ia mencondongkan tubuhnya, dan menatapku tajam. Di genggamannya adalah sebuah
botol bir kosong. Kevin begitu dingin, tak ramah seperti Kevin Fong yang
kukenal.
“Kevin...”
“Cukup, Lee,”
“Kumohon. Kau ini
sahabatku,”
“Tak perlu lagi
mengatakan hal-hal semacam itu,”
“Tapi...”
“Sampai jumpa,
Lee,”
Dengan keras,
Kevin menghantamkan botol bir kosong yang ia pegang ke kepalaku sampai botol
itu pecah. Bisa kurasakan kepalaku berdarah hebat. Kesadaranku mulai berkurang
dan pandanganku semakin kabur. Aku hanya bisa mendengar orang-orang itu pergi dengan
tawa dan cemoohan mereka, dengan deruan motornya yang nyaring, dan kemudian
keadaan kembali sunyi seperti awal. Aku menangis kesal dan marah. Aku kecewa
dengan Kevin, sahabatku sejak dulu. Kenapa ia tega mengkhianatiku? Kalau benar
ia sahabatku, kenapa Kevin bahkan tega membiarkanku dianiaya seperti tadi? Ia
bahkan ikut memberiku hadiah hebat, sebuah hantaman botol bir di kepalaku. Rasanya
tengkorakku seperti retak karena perbuatannya. Emosiku hampir mencapai
batasnya, dan aku sadar bahwa aku tak bisa lagi mengharapkan Kevin untuk
menyadari perbuatannya dan kembali menjadi Kevin Fong yang cerdas dan rajin,
seperti dulu. Emosiku membuatku kuat untuk bangkit.
“Kalau memang kita
tak bisa bersahabat lagi, baiklah, aku takkan mengharapkan untuk bersahabat
lagi denganmu,”
Kuputuskan untuk
melanjutkan perjalanan pulangku, walaupun keadaanku yang bersimbah darah ini. Aku
tak peduli lagi sekarang. Hari ini aku menyadari bahwa seorang sahabat bisa
berubah menjadi seorang musuh, dan hal demikian memang benar adanya. Langkahku
terseok-seok karena betisku yang cedera. Ah, sial! Bagaimana besok aku akan
bekerja? Aku tak sanggup berjalan lebih jauh lagi. Apa aku berteriak meminta
tolong saja? Tapi aku tak mau mengganggu siapapun yang tinggal di sekitar sini.
Atau aku berguling saja di jalanan yang agak menurun ini? Bodoh! Tubuhku sudah
babak belur begini masih mau berguling seperti lembu. Aku harus segera tiba di
rumah, tapi kakiku sudah tak kuat lagi melangkah. Mataku menangkap titik cahaya
dari kejauhan. Benda bercahaya itu bergerak mendekatiku dari arah yang
berlawanan. Semakin lama semakin dekat, dan aku semakin bisa melihat bentuk
benda tersebut. Sebuah taksi akan melintas. Segera aku melambaikan tanganku
agar taksi itu berhenti.
“Taksi!”
Taksi itu berhenti
di sampingku. Dan alangkah terkejutnya supir taksi itu ketika melihatku.
“Astaga! Kau ini!
Kau...”
“Tidak! Aku bukan
hantu!” potongku.
“Lalu, kau ini...”
“Amoy Street!
Sekarang!”
“Tapi kau...”
“Sudah bawa saja!”
Aku langsung masuk
ke dalam taksi dan berbaring di kursi belakang. Supir taksi itu terkejut dengan
perbuatanku, tapi aku memang sudah tak kuat lagi. Tubuhku terasa sangat sakit.
“Pak, apa kita
tidak sebaiknya pergi ke rumah sakit?” tanya supir taksi Cina berusia paruh
baya tersebut.
“Tidak perlu.
Tolong bawa aku ke Amoy Street. Aku ingin pulang saja,” jawabku.
“Tapi anda terluka
hebat,”
“Tidak apa-apa.
Bawa saja aku kesana,”
Supir taksi itu
mempercepat laju mobil. Aku hanya bisa meringis, menahan rasa sakit di sekujur
tubuhku. Orang-orang itu... Terkutuk mereka membuatku seperti ini.
----
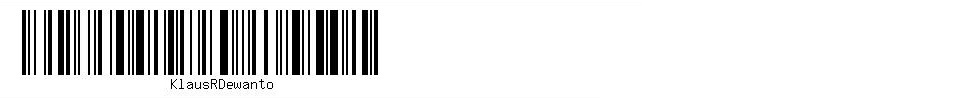
No comments:
Post a Comment
Post some comments, maybe a word two words or a long long paragraph :)