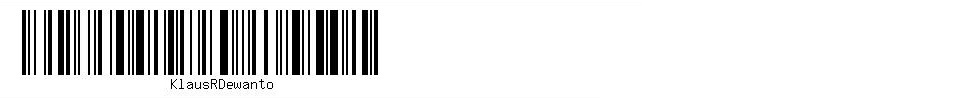Sesak, kuil tua itu dipenuhi oleh cukup banyak turis yang datang berkunjung. Aku harus mengakuinya, Kyoto sangat mengagumkan. Kuil-kuil Shinto dan Buddha berdampingan bersama dalam harmoni tanpa ada pertentangan antar dua keyakinan yang pada dasarnya berbeda. Lagi, pelancong dari ras kaukasius itu semakin memadati kuil-kuil tua yang kelihatannya kesal dengan semakin banyaknya manusia yang mencoba menjajakinya. Teman-teman satu tur sekolah dan guru-guru terjebak di dalam kuil, mencoba mencari jalan keluar sambil terus berusaha mendapatkan udara segar yang bersaing dengan bau dupa dan asapnya. Aku tak begitu suka dengan bau dupa, sehingga 3 menit melihat-lihat bagian dalam bangunan kayu tersebut kurasa sudah cukup. Langit Kyoto kelabu, sesekali ada kabut tipis menghalangi pandangan sejauh kurang lebih 8 meter. Aku berjalan keluar kuil, mencoba menembus dinginnya cuaca. Entah berapa derajat Fahrenheit, tapi udara dingin berhasil menembus jaket dan kaus lengan panjangku kemudian menusuk kulit menuju tulangku yang remuk perlahan. Di tengah-tengah usahaku mendapatkan hangat tubuh agar suhu tubuh kembali optimal, aku masih bisa melihat seseorang duduk di tangga kuil. Ia melihat ke arah danau di depannya. Dari kejauhan di ujung danau ada sebuah jembatan yang menghubungkan Kyoto dengan hingar bingar megapolitan prefektur setelahnya. Matanya terlihat sayu, namun masih ada semangat dari rona wajahnya.
"Ka Bayou ngga masuk?", tanyaku sambil terus menggosok-gosokan tanganku.
"Ngga ah dek..", jawabnya sederhana. Anak yang usianya hampir seumuranku walaupun lebih tua, dengan tinggi yang lagi-lagi hampir sama dan tentunya dia yang lebih tinggi. Kakinya dihentakkan ke anak tangga, entah karena apa. Ia pasti kedinginan. Celana jeans biru tidak bisa membantunya menahan cuaca seperti ini. Jaket hitam aksen ungu tuanya juga takkan membantunya. Ia mulai membatu namun wajahnya masih menunjukkan senyum khasnya. Seseorang yang menyenangkan menurutku.
"Kenapa? Di dalem ada banyak orang loh ka."
"Ngga ah dek. Kan bau dupa. Bayou ngga suka, bikin pusing sama pasti baunya ngga hilang-hilang."
"Iya juga sih ka.."
Salah satu alasan mengapa aku pun tak mau berlama-lama di dalamnya. Untuk menghilangkan bau dupa itu memang cukup sulit. Sudah cukup pengalamanku saat kepergian Opa untuk selamanya. Di ruangan yang cukup besar itu kurasa mereka meletakkan dupa di setiap sudut rumah, di depan altar sudah pasti. Selesai upacara tersebut, aku benar-benar mandi untuk menghilangkan bau dupa yang menjelma menjadi bau tubuhku. Ditambah baunya menempel di bajuku. Bahkan parfum sekelas Giorgio Armani pun kalah dengan bau dari batangan tipis berwarna merah tersebut.
"Kak Bayou lagi bosen ya?"
"Ngga. Lagi asik aja sendirian di luar."
"Kok sendirian? Biasanya sama yang lain. Oh, kakak kan di dalem ya..", aku sedikit bingung karena tidak biasanya dia agak renggang dengan kakakku.
"Ya biarin aja dek, dia kan lagi ikutan tur. Kalo Bayou ngga mau ikutan ah cape. Disini aja jadinya ngeliat-liat pemandangan."
"Apanya yang diliat ka? Sakura belum mekar."
"Ya gapapa. Emangnya harus selalu mekar ya?"
"Tapi kan dingin ka. Masuk ke bis aja yuk ka.."
"Ngga ah. Bayou mau tetep disini aja. Ade aja ke bis duluan, nanti kaka susul sambil bawa takoyaki. Kamu mau kan, dek?"
"Hmm.. Kita beli barengan aja yuk kak. Masih ada beberapa sen nih."
Vendor takoyaki itu berada tak jauh dari kuil. Bahkan dari sini aku masih bisa melihat bis rombongan kami. Sebuah bangku kayu berwarna coklat kehitaman menjadi tempat kami beristirahat sejenak sambil menggigit setiap bagian dari makhluk bertentakel itu.
"Enak ya ka.."
"Iya. Apalagi sepi kaya gini."
"Ade ngga ngerti, ga biasanya Ka Bayou suka sendirian."
"Hmm.. Ada saatnya kamu menyendiri. Kamu ga bisa selalu ada di dalam hingar bingarnya kesibukan atau kesenangan kamu. Terkadang kamu dapat ketenangan jiwa dan kesenangan tersendiri saat kamu sendiri kaya gini."
"Maksudnya?"
"Secara ngga sadar, saat kamu sendiri di tempat kaya gini kamu akan dapetin ketenangan di jiwa kamu. Berfikir juga jadi lebih baik karena otak kita lebih jernih. Kuil ini, menyatu sama alam di sekitarnya. Berhasil membuat atmosfer mengagumkan, khususnya secara pribadi buat Bayou malahan jadi pengalaman spiritual tersendiri. Di tangga kuil tadi, Bayou masih bisa introspeksi diri dan berfikir tentang banyak hal. Bayou juga menyadari banyak hal-hal kecil yang sering dianggap remeh ternyata benar-benar punya pengaruh besar ke hidup Bayou. Di kesendirian juga Bayou menyadari akan pentingnya cinta, sahabat, dan keluarga. Bayou merasa lebih tenang dan lebih sehat di tempat seperti ini. Kebisingan dari mesin-mesin mobil, motor, polusi, cuma bikin Bayou sakit. Tapi disini, walaupun dingin tapi bikin Bayou merasa benar-benar hidup dan memang inilah hidup yang sebenarnya. Klaus, apa yang disebut hidup tidak selalu ketika kamu merasa sangat senang dengan semua kesenangan yang dibuat manusia. Kamu akan benar-benar hidup saat kamu menyatu dengan alam. Saat dingin menusuk tulang kamu, jangan anggap itu sebagai ancaman. Dingin mencoba mendekatkan diri dengan kamu dan saat kamu berhasil beradaptasi dengannya, kamu semakin dekat dengan alam. Alam membuat kamu mengintrospeksi diri kamu, memperlihatkan kesalahan-kesalahan atau sisi negatif yang harus diperbaiki. Alam juga yang membuat kamu mengerti akan kebesaran Tuhan. Bayangkan, apa ade bisa mikir tentang kebesaran Tuhan kalau di tempat yang ribut seperti itu? Atau ketika ada sangat banyak orang? Ya mungkin kamu bisa, tapi tak akan pernah diresapi dan dihayati. Saat kamu sendiri dan hanya bersama alam, di saat itulah kamu menyadari betapa indahnya keajaiban Tuhan."
Aku terdiam dan memaknai kata-kata Kak Bayou. Sebuah paragraf yang cukup panjang mengalir lancar dari mulutnya. Sebuah hal yang tak pernah kukira dari mulut seorang Kak Bayou, orang yang kukenal sebagai seorang yang lincah dan atletik. Kata-katanya terlalu bijak, sehingga aku tenggelam ke dalam pemaknaannya. Penjual takoyaki itu tidak mengerti dengan bahasa yang kami gunakan, sehingga ia kembali menyalakan pemantik apinya dan merokok dalam-dalam. Asap rokok segera hilang ketika perlahan butir-butir air turun dari langit. Hujan. Semakin lama semakin deras. Kami berlari ke arah bis, dan dari arah tangga kuil teman-teman dan guru-guru kami pun berlarian menuju bis. Hujan datang keroyokan, membuat kami ketakutan karena kalah jumlah. Setelah mencari tempat duduk, aku memilih duduk di sebelah Kak Bayou yang ternyata masih menikmati keindahan alam di luar.
"Hujan. Saat hujan, kamu tau ngga de bahwa dunia ini berubah?"
"Maksudnya?"
"Saat hujan, akan ada sesuatu yang berbeda di dunia ini. Kamu bakal tau kalau kamu udah bisa menyatu dengan alam. Bisa satu hati dengan alam. Kalau dilihat dari atas sana mungkin bisa terlihat bedanya."
Aku berada dalam pemaknaan dan kebingungan tersendiri karena kata-katanya. Bis mulai melaju, ke arah jembatan menuju hingar bingar perkotaan. Hujan turun cukup deras. Daun-daun pohon elm berguguran karena berat rintik hujan yang ditanggungnya. Di kaca, butiran-butiran hujan membentuk sungai, bertemu di satu titik dan turun ke bawah. Aku mulai mendapati diriku dalam suhu tubuh yang tepat, sehingga bisa melakukan berbagai pergerakan. Cuaca di dalam bis lebih hangat dibandingkan cuaca di luar. Jendela mulai tertutupi uap air. Aku menuliskan namaku di jendela. Dari kejauhan terlihat kuil tua tadi. Berdiri kaku dengan balutan warna coklat tua kemerahan. Gerbang kuil seolah menyambut pengunjung dengan payung-payung aneka warna. Cukup lelah, aku mengatur sandaran kursi. Kak Bayou kelihatannya tertidur. Aku pun mendapatkan posisi ternyaman dan mulai menutup mataku dalam campuran hingar bingar anak-anak dan suara air hujan di atap bis. Aku merasakannya. Air hujan itu menerpa wajahku halus.
"Ka Bayou ngga masuk?", tanyaku sambil terus menggosok-gosokan tanganku.
"Ngga ah dek..", jawabnya sederhana. Anak yang usianya hampir seumuranku walaupun lebih tua, dengan tinggi yang lagi-lagi hampir sama dan tentunya dia yang lebih tinggi. Kakinya dihentakkan ke anak tangga, entah karena apa. Ia pasti kedinginan. Celana jeans biru tidak bisa membantunya menahan cuaca seperti ini. Jaket hitam aksen ungu tuanya juga takkan membantunya. Ia mulai membatu namun wajahnya masih menunjukkan senyum khasnya. Seseorang yang menyenangkan menurutku.
"Kenapa? Di dalem ada banyak orang loh ka."
"Ngga ah dek. Kan bau dupa. Bayou ngga suka, bikin pusing sama pasti baunya ngga hilang-hilang."
"Iya juga sih ka.."
Salah satu alasan mengapa aku pun tak mau berlama-lama di dalamnya. Untuk menghilangkan bau dupa itu memang cukup sulit. Sudah cukup pengalamanku saat kepergian Opa untuk selamanya. Di ruangan yang cukup besar itu kurasa mereka meletakkan dupa di setiap sudut rumah, di depan altar sudah pasti. Selesai upacara tersebut, aku benar-benar mandi untuk menghilangkan bau dupa yang menjelma menjadi bau tubuhku. Ditambah baunya menempel di bajuku. Bahkan parfum sekelas Giorgio Armani pun kalah dengan bau dari batangan tipis berwarna merah tersebut.
"Kak Bayou lagi bosen ya?"
"Ngga. Lagi asik aja sendirian di luar."
"Kok sendirian? Biasanya sama yang lain. Oh, kakak kan di dalem ya..", aku sedikit bingung karena tidak biasanya dia agak renggang dengan kakakku.
"Ya biarin aja dek, dia kan lagi ikutan tur. Kalo Bayou ngga mau ikutan ah cape. Disini aja jadinya ngeliat-liat pemandangan."
"Apanya yang diliat ka? Sakura belum mekar."
"Ya gapapa. Emangnya harus selalu mekar ya?"
"Tapi kan dingin ka. Masuk ke bis aja yuk ka.."
"Ngga ah. Bayou mau tetep disini aja. Ade aja ke bis duluan, nanti kaka susul sambil bawa takoyaki. Kamu mau kan, dek?"
"Hmm.. Kita beli barengan aja yuk kak. Masih ada beberapa sen nih."
Vendor takoyaki itu berada tak jauh dari kuil. Bahkan dari sini aku masih bisa melihat bis rombongan kami. Sebuah bangku kayu berwarna coklat kehitaman menjadi tempat kami beristirahat sejenak sambil menggigit setiap bagian dari makhluk bertentakel itu.
"Enak ya ka.."
"Iya. Apalagi sepi kaya gini."
"Ade ngga ngerti, ga biasanya Ka Bayou suka sendirian."
"Hmm.. Ada saatnya kamu menyendiri. Kamu ga bisa selalu ada di dalam hingar bingarnya kesibukan atau kesenangan kamu. Terkadang kamu dapat ketenangan jiwa dan kesenangan tersendiri saat kamu sendiri kaya gini."
"Maksudnya?"
"Secara ngga sadar, saat kamu sendiri di tempat kaya gini kamu akan dapetin ketenangan di jiwa kamu. Berfikir juga jadi lebih baik karena otak kita lebih jernih. Kuil ini, menyatu sama alam di sekitarnya. Berhasil membuat atmosfer mengagumkan, khususnya secara pribadi buat Bayou malahan jadi pengalaman spiritual tersendiri. Di tangga kuil tadi, Bayou masih bisa introspeksi diri dan berfikir tentang banyak hal. Bayou juga menyadari banyak hal-hal kecil yang sering dianggap remeh ternyata benar-benar punya pengaruh besar ke hidup Bayou. Di kesendirian juga Bayou menyadari akan pentingnya cinta, sahabat, dan keluarga. Bayou merasa lebih tenang dan lebih sehat di tempat seperti ini. Kebisingan dari mesin-mesin mobil, motor, polusi, cuma bikin Bayou sakit. Tapi disini, walaupun dingin tapi bikin Bayou merasa benar-benar hidup dan memang inilah hidup yang sebenarnya. Klaus, apa yang disebut hidup tidak selalu ketika kamu merasa sangat senang dengan semua kesenangan yang dibuat manusia. Kamu akan benar-benar hidup saat kamu menyatu dengan alam. Saat dingin menusuk tulang kamu, jangan anggap itu sebagai ancaman. Dingin mencoba mendekatkan diri dengan kamu dan saat kamu berhasil beradaptasi dengannya, kamu semakin dekat dengan alam. Alam membuat kamu mengintrospeksi diri kamu, memperlihatkan kesalahan-kesalahan atau sisi negatif yang harus diperbaiki. Alam juga yang membuat kamu mengerti akan kebesaran Tuhan. Bayangkan, apa ade bisa mikir tentang kebesaran Tuhan kalau di tempat yang ribut seperti itu? Atau ketika ada sangat banyak orang? Ya mungkin kamu bisa, tapi tak akan pernah diresapi dan dihayati. Saat kamu sendiri dan hanya bersama alam, di saat itulah kamu menyadari betapa indahnya keajaiban Tuhan."
Aku terdiam dan memaknai kata-kata Kak Bayou. Sebuah paragraf yang cukup panjang mengalir lancar dari mulutnya. Sebuah hal yang tak pernah kukira dari mulut seorang Kak Bayou, orang yang kukenal sebagai seorang yang lincah dan atletik. Kata-katanya terlalu bijak, sehingga aku tenggelam ke dalam pemaknaannya. Penjual takoyaki itu tidak mengerti dengan bahasa yang kami gunakan, sehingga ia kembali menyalakan pemantik apinya dan merokok dalam-dalam. Asap rokok segera hilang ketika perlahan butir-butir air turun dari langit. Hujan. Semakin lama semakin deras. Kami berlari ke arah bis, dan dari arah tangga kuil teman-teman dan guru-guru kami pun berlarian menuju bis. Hujan datang keroyokan, membuat kami ketakutan karena kalah jumlah. Setelah mencari tempat duduk, aku memilih duduk di sebelah Kak Bayou yang ternyata masih menikmati keindahan alam di luar.
"Hujan. Saat hujan, kamu tau ngga de bahwa dunia ini berubah?"
"Maksudnya?"
"Saat hujan, akan ada sesuatu yang berbeda di dunia ini. Kamu bakal tau kalau kamu udah bisa menyatu dengan alam. Bisa satu hati dengan alam. Kalau dilihat dari atas sana mungkin bisa terlihat bedanya."
Aku berada dalam pemaknaan dan kebingungan tersendiri karena kata-katanya. Bis mulai melaju, ke arah jembatan menuju hingar bingar perkotaan. Hujan turun cukup deras. Daun-daun pohon elm berguguran karena berat rintik hujan yang ditanggungnya. Di kaca, butiran-butiran hujan membentuk sungai, bertemu di satu titik dan turun ke bawah. Aku mulai mendapati diriku dalam suhu tubuh yang tepat, sehingga bisa melakukan berbagai pergerakan. Cuaca di dalam bis lebih hangat dibandingkan cuaca di luar. Jendela mulai tertutupi uap air. Aku menuliskan namaku di jendela. Dari kejauhan terlihat kuil tua tadi. Berdiri kaku dengan balutan warna coklat tua kemerahan. Gerbang kuil seolah menyambut pengunjung dengan payung-payung aneka warna. Cukup lelah, aku mengatur sandaran kursi. Kak Bayou kelihatannya tertidur. Aku pun mendapatkan posisi ternyaman dan mulai menutup mataku dalam campuran hingar bingar anak-anak dan suara air hujan di atap bis. Aku merasakannya. Air hujan itu menerpa wajahku halus.