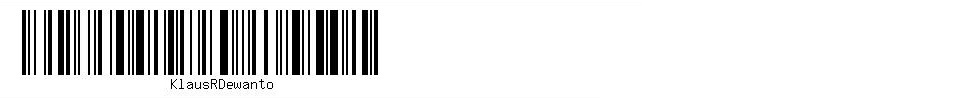“Kenakan helm
dengan benar, Timothy!”
Paman Richard
menegur adikku. Kubetulkan helm yang dikenakan adikku. Nampaknya tali
pengencangnya longgar sehingga dagunya tak bisa terlindungi oleh pelindung
dagu. Sekali tarik tali pengencangnya dan... ya, kepala Timothy terlindungi
sekarang.
“Paman, kami
berangkat dulu,” ujarku.
“Hati-hati, Lee.
Jangan mengebut!” pesan paman.
Kulaju motorku
dengan kecepatan sedang. Keluar dari Amoy Street, kupacu motorku di jalan yang
lebih besar. Pagi ini nampak lebih lengang dari biasanya. Tak banyak hiruk
pikuk kendaraan roda empat yang biasa memenuhi jalan ini.
“Jalanan pagi ini
sepi juga. Benar, ‘kan?” ujarku. Timothy menepuk pundakku.
“Ada apa?”
tanyaku.
Aku melirik ke arah
spion kanan. Adikku mengangkat jempolnya sebagai tanda setuju. Aku tertawa
kecil melihat tingkah adikku.
“Ah, kau ini.
Salah sendiri tak mau bicara, jadi sulit ‘kan berbincang-bincang seperti ini,”
Adikku memukul
bagian belakang helmku. Pukulannya terasa ke kepalaku. Aku terkejut, tapi aku
lantas tertawa karena aku tahu itu pasti balasan dari Timothy untuk
perkataanku.
“Hahahaha! Cukup,
Timmy. Jangan pukul lagi helmnya,”
Kulirik lagi spion
kanan motor ini. Timothy nampak senang melihat-lihat suasana Singapura pagi
ini. Langit pagi yang nampak mendung tetapi masih cerah, ditambah lagi suasana
lalu lintas yang tak padat membuat perjalanan dari rumah menuju sekolah terasa
cukup nyaman. Kusadari tangannya sedari tadi tak bisa diam memainkan ponselnya.
Timothy bisa jatuh terjungkal jika sewaktu-waktu aku harus melakukan pengereman
mendadak.
“Timmy, masukkan
ponselmu ke saku jaketmu dan berpeganganlah,” ujarku, “Kau bisa jatuh
terjungkal ketika aku melakukan pengereman mendadak jika kau tak berpegangan,”
Timothy nampak
memasukkan ponselnya ke dalam saku jaketnya. Ah, ia rupanya patuh juga pada
ucapanku, tapi tangannya tetap tak berpegangan pada sisi pegangan di jok
belakang motor. Aish, anak ini...
“Timmy, kau bisa
jatuh. Berpeganganlah atau betulkan posisi dudukmu. Atau, majulah sedikit ke
dekatku dan pegang sisi pinggangku,” ujarku.
Timothy duduk
lebih maju ke dekatku dan ia malah memegang perutku, bukan pinggangku. Kontan
saja aku kaget dan kegelian.
“Timmy! Lepaskan!
Maksudku genggam sisi badanku, tapi jangan benar-benar seperti memelukku.
Genggam saja jaketnya atau genggam kedua saku jaketku di tiap sisinya,” jelasku.
Timothy terdengar
tertawa kecil. Aku ikut tertawa juga mendengar tawanya. Ah, adikku ini.
Nampaknya ia memang ingin bercanda denganku. Tapi, bercanda seperti itu ketika
aku sedang menyetir bukanlah hal yang tepat. Bisa saja konsentrasiku pecah dan
motor ini oleng karena aku merasa kegelian di bagian sisi perutku.
“Kapan-kapan kau
kuajari cara mengendarai motor. Kau mau?” tanyaku.
Aku tak tahu
jawaban Timothy apa karena aku tak melirik lagi spion kananku. Di hadapanku ada
persimpangan dan lampu lalu lintas berubah menjadi merah. Beruntunglah aku
mendapat barisan terdepan. Segera kuhentikan motorku dan menoleh ke belakang.
Timothy tersenyum jahil padaku.
“Jangan lakukan
hal itu lagi. Geli rasanya. Kau ingin kukelitiki juga nanti ketika kau sudah
pulang, hah?” tegurku. Timothy tertawa.
“Tak mau. Lagipula tadi kau yang suruh aku memegang
pinggangmu,” jawab Timothy.
“Pinggang, bukan
perut. Lagipula kau malah memelukku dan selain geli, aku juga jadi sesak. Ikat
pinggangku nampaknya terlalu kencang kuatur,”
Satu buah motor
lalu ikut mengantri di belakang motor kami. Di sampingku ada sebuah mobil sedan
berwarna merah mengkilat yang mengingatkanku dengan mobil yang serupa yang
selalu diparkir di samping tembok belakang restoran tuan Edvard. Mobil yang
bagus. Butuh berapa tahun kira-kira agar aku bisa membelinya sendiri? Sedang
asyik melamun, helmku dipukul lagi dari belakang. Aku menoleh ke arah spion dan
kulihat Timothy nampak pucat. Aku langsung menoleh ke belakang dan Timothy begitu
ketakutan.
“Timmy? Ada apa?”
tanyaku kaget.
“Lee, kau
mencariku?”
“Steve?!”
Mobil merah di
sampingku melaju, dan diikuti oleh Steve di belakangnya. Dan ketika ia melewati
kami, sesuatu yang sangat cepat terjadi. Entah bagaimana tapi tiba-tiba
terdengar pekikan Timothy dan kurasakan sebuah benda tajam dengan cepat
menyayat betis kananku. Aku memekik kaget. Motor besar yang dikendarai Steve lalu
melaju begitu saja dengan cepat. Rasa perih di betisku begitu membabi buta. Kupejamkan
mataku menahan rasa sakit. Astaga, apa yang ia lakukan?
“Timmy, kau tak
apa-apa?” tanyaku khawatir.
Aku lalu menoleh
ke belakang untuk memeriksa keadaan adikku. Wajahnya nampak menahan sakit. Di
belakangku mulai ada antrian kendaraan yang mulai mengklaksoniku. Segera kupacu
motorku melewati persimpangan tersebut sambil dengan hati-hati mencari apotek
terdekat.
“Timothy, jika kau
melihat apotek segera beritahu aku,” ujarku.
Sambil terus
menahan sakit, aku terus memacu motorku. Sial, Steve pasti tadi mengeluarkan
benda tajam untuk dengan sengaja melukai kami. Entah apapun itu bendanya,
kurasa luka di betisku cukup dalam. Atau bisa jadi ia dengan sengaja hendak
benar-benar memutuskan betisku. Bajingan.
“Koh,” bisik Timothy.
“Ya? Apa kau
melihatnya?” tanyaku.
Tangan Timothy
menunjuk ke sebuah apotek di sisi kiri jalan besar ini. Aku segera menepikan
motorku dan memarkir motorku. Kumatikan mesin motor dan turun dari motor. Ah,
sial! Sakit sekali rasanya ketika kaki kananku memijak jalan. Celana jeansku
terkoyak di bagian betis dan di bagian yang sobek itu nampak basah oleh cairan
berwarna merah gelap pekat. Aku mengangkat celana jeansku dan kulihat luka
sayatan di betisku cukup dalam. Kupegang luka itu dan aku meringis keras karena
rasa perih yang kurasa.
“Sialan. Bajingan
itu,” umpatku.
Aku lalu memeriksa
adikku. Luka yang sama didapat adikku di betis kanannya, hanya saja tak sedalam
luka yang kudapat. Darahnya mengalir dari luka sayatan di betisnya, dan
mengotori kaus kaki putihnya serta meninggalkan bercak di sepatu basketnya.
“Sangat sakitkah?”
tanyaku. Timothy mengangguk.
Aku lalu membawa
adikku masuk ke dalam apotek. Apoteker wanita yang bertugas disana terkejut
melihatku dan Timothy yang berdarah di bagian betis. Tanpa pikir panjang ia
langsung mencari apa yang kami butuhkan, lalu menghampiri kami dengan
gulungan-gulungan perban dan obat antiseptik.
“Bagaimana ini
bisa terjadi?” tanya apoteker tersebut.
“Ceritanya sangat
panjang. Sekarang, kumohon tolong kami. Bisakah ini semua selesai sebelum jam
delapan? Kami bergegas menuju sekolah. Adikku tak boleh terlambat masuk
sekolah,” tepisku.
“Ah, baiklah kalau
begitu,”
Apoteker tersebut
dengan gesit mengobati luka di betis Timothy. Timothy nampak kesakitan dan
meringis ketika apoteker tersebut membalut betisnya dengan perban. Aku
mengobati sendiri luka di betisku karena tak mau membuang-buang waktu lagi.
Timothy tak boleh sampai terlambat ke sekolah. Aku tahu betisnya terluka, tapi
bagaimanapun juga Timothy masih kuat untuk mengikuti pelajaran di sekolah. Ia
tak boleh sampai bolos.
----
Tiba juga akhirnya
kami setelah perjalanan yang memakan waktu lama karena insiden yang tak pernah
kami harapkan itu. Kuparkir motorku di tempat parkir yang ada. Setelah turun
dari motor, aku membantu Timothy turun dari motor dan kupapah ia sampai atrium
sekolah.
“Sudah, sampai disini saja,”
“Kau yakin kau tak
apa-apa?” tanyaku ragu. Timothy mengangguk.
“Tenang saja. Kelasku tak jauh. Kakak pulang saja. Aku
akan baik-baik saja,”
“Tapi, kau masih
terpincang-pincang. Aku khawatir jika lukanya memang dalam dan kau malah tak
bisa berjalan,”
“Jangan khawatir, Koh. Aku akan baik-baik saja. Lagipula
aku akan bertemu teman-temanku. Mereka akan menolongku,”
Aku menatap
Timothy khawatir, tapi bagaimanapun juga aku harus melatihnya agar mandiri. Toh
ia sendiri yang bilang bahwa ia akan baik-baik saja. Setelah pamit, Timothy
berjalan terpincang-pincang masuk ke dalam sekolah. Dari jauh kupantau ia.
Kulihat beberapa anak menghampirinya. Mereka menanyainya dengan banyak
pertanyaan.
“Timothy, kau
baik-baik saja?”
“Kakimu kenapa?”
“Lihat, ada noda
darah di kaus kaki dan sepatumu!”
“Timothy, apa yang
terjadi?”
Aku menghela nafas
lega. Ah, syukurlah kalau begitu. Teman-teman Timothy begitu perhatian dan
membantu Timothy berjalan. Kukira awalnya Timothy tak punya teman karena ia tak
mau bicara, tapi nyatanya temannya cukup banyak. Aku tak seharusnya meragukannya
seperti itu. Aku tak perlu terlalu mengkhawatirkan Timothy dan sekarang aku
harus kembali pulang untuk bersiap-siap. Ya, aku harus pergi bekerja.
----