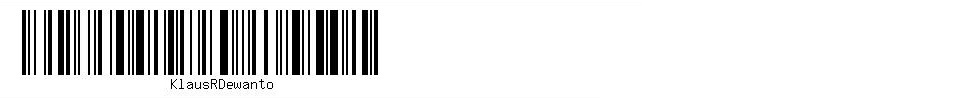Tiba di rumah, perlahan
kubuka pintu menuju garasi di samping toko paman Richard. Lampu garasi masih menyala. Pasti tadi paman
buru-buru pergi ke rumah sakit. Aku berbalik dan kulihat Rei berdiri menatapku
bingung.
“Lee, kau tak apa-apa?”
tanyanya. Aku mengangguk pelan.
“Masuklah. Aku
akan segera mengunci pintunya,” jawabku.
Rei masuk, lalu
segera kukunci pintu. Kami lalu menaiki tangga untuk masuk ke rumah. Kulihat ruang
keluarga nampak berantakan. Ada pecahan cangkir kopi di lantai, dengan koran
yang halamannya berserakan di atas meja kopi. Kurasa paman sedang membaca koran
ketika mendengar berita itu dan ia panik, sehingga ia tak sengaja menjatuhkan
cangkir kopinya. Di asbak ada dua puntung rokok yang telah menghitam. Jam besar
di sudut ruangan menunjukkan pukul setengah dua belas malam. Seandainya aku
bisa memutar ulang waktu, tapi itu pasti tak akan mungkin.
“Lee, kau
beristirahatlah. Segera naik ke kamarmu. Biar aku yang membereskan kekacauan
disini,” ujar Rei.
“Tapi...”
“Sudahlah, tenang
saja. Nanti aku akan tidur di ruang keluarga di lantai dua sambil menonton
televisi. Kau naik ke kamarmu saja. Hmm... Nampaknya paman Richard yang
menjatuhkan cangkir kopinya. Sayang sekali padahal cangkirnya bagus,” potong
Rei.
Aku menggeleng
pelan.
“Tidak. Biar aku
saja yang membereskan,”
“Kau harus
beristirahat. Lee, kau nampak lelah dan terpukul. Aku tahu bagaimana
perasaanmu. Apa yang kau rasakan sama seperti ketika aku kehilangan ayahku.
Mungkin bedanya, Timothy berhasil diselamatkan sementara ayahku... Ya, kau tahu
ayahku sekarang sedang tidur di pangkuan Tuhan. Berlarut-larut dalam kesedihan
seperti ini hanya akan membuatmu semakin sakit. Kau harus beristirahat. Kau
mengerti?”
Aku mengangguk
pelan lalu pergi ke kamarku di lantai dua. Tiba di kamarku, segera kututup
pintu kamarku, kukunci, dan kusandarkan tubuhku ke pintu kamarku. Air mataku
meleleh lagi. Lututku lemas. Perlahan aku menjatuhkan tubuhku dan duduk
bersandar di pintu. Rasanya sakit sekali mengetahui orang yang kusayangi,
adikku, sekarang terbaring lemah di rumah sakit. Kondisinya yang sangat kritis
membuatku dibayang-bayangi ketakutan antara hidup dan matinya. Aku tahu Timothy
anak yang kuat, tapi bagaimanapun ia tetap adik kecilku. Bagaimana jika ia tak
kuat menahan sakit itu? Bagaimana jika ia menyerah? Atau, bagaimana jika ia
sudah terlanjur membenciku dan lebih memilih untuk bersama ibu dan ayah
daripada kembali bersamaku? Berapa lama aku akan kuat hidup tanpa orang-orang yang
kusayangi? Berapa banyak lagi orang-orang yang harus kulihat pergi dengan mata
kepalaku sendiri? Masih bisakah aku tegar ketika akhirnya aku yang harus
menebar abu jenazah adikku di laut?
Di bawah tempat
tidur, kulihat sebuah boks berwarna hitam. Aku merangkak ke dekat tempat tidur
dan tanganku merogoh boks tersebut. Rupanya itu adalah boks sepatu basket
Timothy. Boks itu kosong, hanya ada secarik kertas yang sudah kumal. Aku
membentangkan kertas tersebut dan membaca tulisannya.
“Jangan beritahu Lee tentang sepatu ini. Dia memang
menyebalkan. - Paman Richard,”
Aku tersenyum
sendiri membaca tulisan tersebut. Kumasukkan kembali kertas itu ke dalam boks
sepatu Timothy dan kumasukkan lagi boks tersebut ke bawah tempat tidur. Aku
terdiam sejenak. Kurasa selama ini aku sudah begitu egois dan keras kepala.
Keegoisan dan kekeraskepalaanku membuat Timothy akhirnya menjadi korbannya. Aku
hanya tak ingin memberatkan siapapun, tetapi mungkin caraku salah selama ini.
Aku menghela nafas dan mulai menyesali apa yang selama ini kulakukan.
Seandainya aku tak seperti itu sejak dulu, tetapi semua sudah terlanjur
terjadi. Timothy pasti selama ini memendam rasa kesal padaku.
Tanganku
mencengkram erat tempat tidurku dan aku berusaha bangun. Kulihat sekeliling
kamarku. Meja belajar Timothy nampak berantakan. Lampu belajarnya masih menyala,
menerangi daerah sekitarnya. Aku berjalan menuju meja belajarnya. Kulihat buku
tugas Timothy berada di atas meja belajarnya. Kubuka halaman demi halaman buku
tugasnya. Timothy anak yang rajin. Nilai-nilainya tak pernah buruk. Di salah
satu tugas matematikanya, ia mendapat nilai delapan puluh enam. Kulihat hasil
pekerjaannya. Terdapat beberapa nomor soal yang ditandai salah. Aku tersenyum
sambil terisak melihat jawaban-jawaban yang salah itu.
“Bodoh. Sinus dari
dua ratus tujuh puluh saja tak tahu. Seharusnya minus satu,”
Kututup buku
tugasnya dan kutaruh kembali di atas meja belajarnya. Di atas meja belajarnya
juga terdapat beberapa lembar uang yang tadi ia berikan dan kaus Nike berwarna
biru laut tua yang sempat menjadi bahan pertengkaran kami tadi sore. Tanganku
gemetaran mengambil kaus tersebut. Kuremas kaus tersebut dan aku semakin
terisak. Kutengadahkan kepalaku agar air mataku tak turun, tapi itu tak
berhasil.
“Timothy...”
Tangisku meledak
lagi. Aku jatuh berlutut. Di atas meja belajarnya, aku terisak hebat. Tanganku
terus memeluk kaus milik Timothy itu. Berulang kali aku memanggilnya, dan
semakin aku takut kehilangan adikku. Aku pasti nampak sangat menyedihkan
sekarang. Aku menangis seperti anak kecil yang kehilangan mainannya. Tapi
adikku bukanlah sebuah mainan. Ia adalah seorang yang sangat aku sayangi, jadi
perasaan kehilangan itu pasti akan jauh lebih menusuk. Memoriku memutar ulang
kejadian tadi sore dan juga memutar semua momen-momen indah yang aku dan adikku
lakukan. Bermain piano bersama sambil bernyanyi, berolahraga pagi, bermain
basket, menikmati es krim potong di taman bersama, menghabiskan ramen,
berjalan-jalan, bersama paman merayakan ulangtahunnya yang ke-empat belas,
sungguh demi apapun aku tak ingin kehilangan adikku. Aku akan lakukan apapun
asalkan adikku mau memaafkanku. Aku akan lakukan apapun untuk membuat Timothy
kembali tersenyum, bahkan agar ia bisa kembali bicara seperti dulu. Aku akan
lakukan apapun asalkan adikku masih bisa hidup. Aku tak ingin ia pergi. Aku tak
ingin kehilangan adikku. Sungguh, aku tak ingin itu terjadi.
“Timothy... Jangan
pergi,”
----