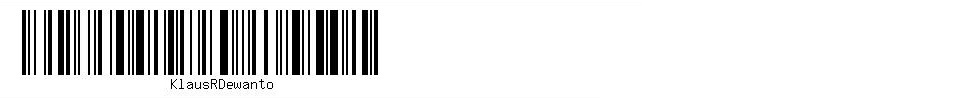Paman kedatangan
stok-stok terbaru untuk tokonya. Aku membantu paman menaruh kardus besar berisi gelas-gelas plastik kecil ke dalam sebuah rak besar.
“Lee, jangan lupa
kardus berisi piring plastik ini juga kau taruh dengan rapi. Biar aku yang
mengeluarkan isinya,” ujar paman.
“Baiklah, paman,”
jawabku.
Paman melayani
petugas distribusi yang datang dengan ramah, sementara aku agak kewalahan
dengan stok-stok yang baru datang ini. Ada banyak barang disini dan aku bingung
yang mana yang harus kubereskan terlebih dahulu. Hmm... Bagaimana jika aku
mulai dengan membereskan botol-botol kecap manis ini, lalu merapikan stok pasta
gigi ke lemari, dan kemudian membereskan piring plastik ini?
“Lee, bagaimana?”
tanya paman.
“Aku sedang
merapikannya, paman,” jawabku.
“Hmm... Kau
nampaknya tak pergi bekerja hari ini,”
“Aku ‘kan libur
pada hari Jumat,”
“Kau terlalu rajin
bekerja, sih. Edvard saja bosan melihatmu,”
“Ah, paman bisa
saja,”
“Lee, bagaimana
hubunganmu dengan Timothy?”
“Kami? Entahlah,
kurasa mulai membaik,”
“Kemarin aku
membelikannya mainan baru. Timmy nampak bosan di kamarnya, jadi kuminta pacarmu
mengantarku mencari mainan untuk adikmu. Tiffany anak yang baik dan sopan
kepada orang tua. Ia benar-benar membantuku,”
“Paman, apa itu
tidak merepotkan?”
“Merepotkan
apanya?”
“Membelikan
Timothy mainan mahal?”
“Aish, kau ini
masih saja menyebalkan! Lagipula aku memakai uangku, bukan uangmu! Kau mau
kulempar dengan gayung plastik ini?!”
“Tidak! Jangan
paman! Aku ‘kan hanya bertanya saja,”
“Kau ini. Awas jika
kau bertanya seperti itu lagi,”
“Ya, paman...”
“Oh ya, hari ini
kau tak perlu mengantar Timothy ke tempat les pianonya. Aku telah memberitahu
Tiffany bahwa Timothy belum kuizinkan pergi keluar rumah. Jadi siang ini
Tiffany akan datang, dan aku harap kau bisa menemani adikmu berlatih piano,”
“Hmm... Baiklah,”
“Dan juga, Timothy
masih dalam keadaan yang belum benar-benar baik. Kau jangan dulu mengajaknya
bepergian,”
“Apa?”
“Ya, kau tak boleh
mengajaknya bepergian. Bagaimana jika luka adikmu terbuka lagi?”
“Tapi aku hari ini
sebenarnya berencana mengajak Timothy pergi ke...”
“Tidak! Timmy
harus beristirahat!”
Aku meringis
kesal.
“Ah, setelah ini
kau naik saja ke rumah. Tolong cuci baju-baju yang belum sempat kucuci subuh
tadi, setelah itu kau boleh beristirahat,”
“Ah, paman ini...”
Aku segera
menyelesaikan tugasku dan setelah beres, segera aku naik ke rumah, meninggalkan
paman yang sedang sibuk di toko. Duduk aku di kursi piano sambil mengatur
nafasku.
“Bagaimana ini? Hari
ini aku libur dan ini hari yang tepat,” batinku.
Atau lebih baik
aku diam-diam saja membawa Timothy pergi? Tapi percuma juga bila ia susah
dibujuk...
Tapi aku harus
bisa membujuknya!
----
“Rentangkan lebih
lebar jemarimu. Ya, seperti itu,”
Timothy nampak
kesakitan ketika ia berusaha merentangkan jemarinya lebih lebar. Di hadapannya
adalah notasi ‘La Campanella’ karya Frans Liszt yang ia coba pelajari. Karya
klasik itu nampak sulit, terlihat dari betapa Timothy berjuang dengan sekuat
tenaga untuk bisa merentangkan jarinya agar lebih mudah menjangkau beberapa
tuts yang letaknya terpisah cukup jauh satu sama lain.
“Nampaknya sulit,”
aku berkomentar.
“Memang, tetapi
adikmu begitu tekun berlatih. Jika ia rajin berlatih, jarinya akan terbiasa
dengan rentang tuts yang jauh ini,” jawab Tiffany.
“Kau pernah
memainkan lagu ini?”
“Pernah, tapi baru
tiga kali aku memainkannya. Lagu ini terlalu riskan untukku. Kelingkingku
pernah cedera ketika memainkan lagu ini,”
“Jarimu terkilir?”
“Ya, begitulah.
Aku jadi tak bisa mengajar selama seminggu,”
“Jika jarimu
terkilir ketika bermain piano, jadi kau tak bisa bermain selama seminggu?”
“Tidak juga.
Tergantug bagaimana kondisi lukamu,”
“Kalau begitu
jangan berikan Timothy lagu-lagu yang riskan,”
Aku bangkit
menghampiri Tiffany dan Timothy, hendak menahan Timmy agar tak memainkan
lagu-lagu yang berpotensi mencederai jemarinya. Tiffany menahanku; ia menarik
lenganku.
“Lee, biarkan!
Lihat,”
Aku memperhatikan
Timothy yang rupanya sedang memainkan lagu itu dari awal. Ia memainkannya
pelan-pelan, dan aku begitu kagum karena ia bisa memainkannya dengan baik
sampai baris ke empat.
“Timmy! Kau
memainkannya dengan baik! Walaupun temponya masih sangat lambat, tapi kau
memainkannya dengan baik, dan hanya sedikit nada yang keliru! Ah, aku bangga
padamu!” Tiffany merangkul Timothy dan memujinya.
“Adikku akan jadi
penerus Mozart,” tambahku.
“Adikmu hebat,
Lee! Kau bisa bermain seperti dia?”
“Ah, jangan
ditanya! Tentu saja aku tak bisa,”
“Hahahaha! Kau
juga harus berlatih, Lee! Kau sebenarnya punya bakat, tetapi jarang kau latih.
Sayang sekali jadinya,”
“Ya, mungkin nanti
aku akan mulai berlatih lagi,”
Jam besar
berdentang dua kali. Ah, sudah jam dua rupanya. Aku harus bergegas karena aku
akan mengajak Timothy pergi ke suatu tempat. Setengah berlari aku naik ke
kamarku, berganti baju, mengambil jaket dan kaus Timothy yang dibelikan oleh
Tiffany, lalu membawanya turun. Timothy dan Tiffany terkejut denganku yang
nampak terburu-buru.
“Lee, ada apa? Kau
berganti baju?” tanya Tiffany.
“Ayo bergegas.
Timmy, ganti bajumu,” tegasku.
“Apa? Hey, kau mau
membawa adikmu kemana?” tanya Tiffany kaget.
“Aku sudah
berjanji mengajaknya pergi saat itu, tapi hujan turun sehingga kami tak jadi
pergi. Lebih baik sekarang saja aku mengajaknya pergi,” jawabku.
“Tapi pamanmu
melarang Timothy pergi kemanapun,”
“Tapi aku tak
punya waktu lagi!”
“Memangnya kau tak
bisa mengajaknya pergi di akhir pekan saja?”
“Aku sudah
meluangkan waktuku untuk Timothy. Kebetulan hari ini aku memang tak bekerja. Ayo,
Timmy. Ganti bajumu,”
Timothy menggeleng
pelan.
“Ada apa? Kenapa
kau tak mau? Kumohon, selagi aku tak bekerja hari ini,” tanyaku kaget.
“Bagaimana jika paman marah?”
“Aku yang akan
dimarahi, bukan kau. Ayolah, kumohon...”
“Lee, kau jangan
mengambil resiko!” tegur Tiffany.
“Kau tak mau
menolongku?”
Tiffany menatapku
tak percaya.
“Kau... Kau mau
membawanya kemana?”
“Ke tempat yang
sudah kujanjikan padanya,”
“Kemana? Apakah
tempat itu berbahaya untuknya?”
“Tidak. Ayo,
Timmy. Ganti pakaianmu,”
“Tak mau,”
“Kumohon! Aku
berjanji setelah ini aku tak akan mengganggumu lagi jika kau merasa aku
mengganggumu,”
“Aku tak mau pergi,”
“Kumohon, Timmy.
Hanya hari ini saja,”
Timothy sempat
meronta ketika aku memaksanya melepas kausnya, tetapi akhirnya ia mengalah. Aku
memintanya berganti baju dan mengenakkan jaketnya. Aku sendiri heran, Timothy
tak mengelak atau menghindariku. Apa mungkin Timothy sudah mau berkomunikasi
lagi denganku?
“Kau sudah siap?”
tanyaku. Timothy mengangguk pelan.
“Ayo, Tiffany.
Kita berangkat sekarang,”
“Apa? Lee, kau
ingin dimarahi habis-habisan oleh pamanmu?”
“Tak ada jalan
lain. Ayolah!”
“Tapi...”
“Kau mau
membantuku atau tidak?”
Tiffany nampak
ragu. Ia tertunduk lesu, lalu menatapku.
“Pastikan pamanmu
tak ikut memarahi adikmu karena kekeraskepalaanmu ini,”
Aku mengangguk
setuju.
----
Perjalanan menuju
tempat yang kumaksud memakan waktu agak lama. Timothy sampai tertidur di dalam
bis. Ia bersandar pada Tiffany. Aku melirik Tiffany yang nampak terkejut karena
Timothy tertidur pulas bersandar ke sisi kanannya.
“Berat?” tanyaku.
“Tidak. Tak
apa-apa, Lee. Hanya saja posisinya bersandar padaku membuatku agak kurang
nyaman,” jawabnya.
“Dorong ia ke
arahku agar ia bersandar padaku,”
“Tak usah, Lee.
Kasihan adikmu, ia pasti kelelahan,”
Bis akhirnya tiba
di perhentian, namun Timothy masih belum bangun. Aku akhirnya menggendongnya
keluar bis. Tiffany nampak masih bingung dengan tujuan kami.
“Lee, kau akan
membawa kita kemana?” tanyanya.
“Kau lihat saja
nanti. Sekarang ayo kita membeli tiket MRT,” jawabku.
Aku bergegas
menuju tempat pembelian tiket MRT untuk membeli tiga tiket untuk kami. Tiffany
nampak masih bingung tapi aku tak peduli, selama ia masih terus mengikutiku.
Kami masuk ke dalam kereta dan kereta dengan cepat membawa kami ke sebuah pulau
yang berjarak tak jauh dari pulau Singapura. Tiffany mulai sadar kemana aku
akan membawa mereka. Ia menatapku bingung.
“Lee, kau akan
membawa kami ke Universal Studio?” tanyanya.
“Tidak,” jawabku.
“Lantas?”
“Kau lihat saja
nanti,”
“Lee, kau jangan
seperti ini! Kau tahu, sekarang paman Richard pasti marah padamu karena
mengetahui kau membawa adikmu pergi tanpa seizinnya!”
“Ponselku sudah
kumatikan,”
“Bagaimana jika ia
menghubungiku?”
“Paman tak tahu
nomor ponselmu,”
“Lalu ponsel
adikmu?”
“Sengaja
kutinggalkan di atas piano,”
“Lee! Kau ini
keterlaluan!”
“Kau mau
membantuku atau tidak? Kau tak tahu rencanaku, ‘kan?”
“Tapi bukan begini
caranya!”
Monorel telah
berhenti dan aku bergegas keluar dari monorel, berjalan menggendong adikku
sampai tempat yang kumaksud. Tiffany mengikutiku di belakang tanpa tahu apa
maksudku sebenarnya. Ia terdengar menggerutu dan mengomeliku, tapi aku acuhkan
saja agar ia tahu sendiri maksudku membawa adikku kemari.
“Lee, kau
mendengarkanku atau tidak?!”
“Aku mendengarmu,”
“Lalu jawab
pertanyaanku!”
“Kau akan
mendapatkan jawabanmu nanti,”
“Kau ini
menyebalkan! Sekarang aku mengerti betapa keras kepala dan egoisnya kau!”
“Tiffany, kau akan
tahu maksud dari apa yang kulakukan ini nanti,”
“Tapi kau berbuat
seenaknya seperti ini, membawa adikmu yang masih sakit pergi, dan melanggar
larangan pamanmu!”
“Kau sendiri
memangnya tak pernah melanggar peraturan sekolah ketika kau masih bersekolah
dulu?”
Aku menghentikan
langkahku lalu berbalik. Tiffany menatapku tajam. Kali ini matanya tak
tersenyum padaku.
“Kenapa kau jadi
bertanya seperti itu?”
“Kau pernah ‘kan
melanggar peraturan ketika kau bersekolah dulu? Katakan padaku kau pernah kabur
dari sekolah bersama Luna dan teman-temanmu untuk berbelanja di mal lalu pulang
hampir tengah malam,”
“Bagaimana kau
tahu itu?”
“Luna banyak
bercerita tentangmu. Sekarang, apa bedanya kau dengan aku? Kita sama-sama
pernah melanggar aturan,”
“Tapi itu dulu,
Lee. Sekarang aku bukan anak kecil lagi,”
“Aku juga bukan
anak kecil lagi sekarang, dan aku sadar aku melakukan hal ini. Kau tahu,
sesuatu terjadi karena sebuah alasan. Aku tak melakukan ini begitu saja. Aku
harus menepati janjiku pada adikku,”
“Tapi...”
“Kau akan mengerti
maksudku nanti,”
Tiffany akhirnya
terdiam. Aku melanjutkan langkahku dan Tiffany mengikutiku. Semakin dekat aku
dengan tempat yang kutuju, semakin keras terdengar suara deburan itu, dan desir
angin yang menyejukkan. Kini di depanku adalah lautan lepas, dengan deburan
ombak dan angin yang berhembus lembut membelai wajahku.
“Pantai Tanjong?
Kau mau apa disini?” tanya Tiffany.
“Mempertemukan
adikku dengan hal yang ia rindukan,” jawabku.
Aku lalu membangunkan
Timothy yang masih tidur di gendonganku. Ia menggeliat pelan sebelum membuka
matanya.
“Timmy, bangunlah.
Lihat,”
Timothy terbangun.
Aku lalu menurunkannya. Ia berdiri di sampingku menatap laut yang ada di
hadapannya. Matanya terbuka memandang ombak yang berkejaran untuk memeluk pasir
putih yang terhampar.
“Timmy, kau ingat
kau pernah memintaku membawamu ke laut? Malam itu aku membawamu ke atap dan
menunjukkanmu pemandangan malam hari. Kau melihat laut dan kau menangis karena
kau merindukan ayah dan ibu. Kau ingat, kita bersama-sama menebar abu jenazah
ayah dan ibu saat itu walaupun bukan di pantai ini, di laut di hadapan kita
ini. Tapi kau tahu, kurasa laut saling bersatu dan bagaimanapun juga seperti
yang kau ketahui, ayah dan ibu telah bersatu dengan laut. Aku tak bisa membawa
mereka kembali untukmu, jadi aku membawamu untuk bertemu mereka disini. Kau
merindukan mereka, bukan?”
Mata adikku mulai
berkaca-kaca. Ia melepas sepatunya lalu mulai berjalan ke tepi pantai. Ia
menginjak butiran-butiran pasir putih, lalu terkena terjangan ombak kecil yang
tiba ke pantai. Ia berjalan semakin ke tengah, dan ketika air laut sudah
setinggi pinggangnya, ia terhenti. Aku melepas sepatuku dan menyusulnya. Aku
berhenti beberapa meter darinya, membiarkannya melepas rindunya yang cukup lama
ia pendam.
“Ibu... Ayah...”
Timothy memanggil
ibu dan ayah. Kudengar ia lalu menangis dan terisak. Semakin lama isakannya
terdengar semakin keras. Aku merasa iba pada adikku. Miris sekali mendengarnya
menangis seperti ini.
“Aku merindukan
kalian! Kenapa kalian tega meninggalkan kami secepat ini!”
Adikku
menampar-namparkan tangannya frustasi ke permukaan air sambil tetap terisak.
Lama kelamaan, Timothy justru mengungkapkan kekesalannya karena kepergian kedua
orangtua kami yang terlalu cepat.
“Kenapa kalian
tega melakukan ini! Kami masih membutuhkan kalian tapi kalian meninggalkan kami
ketika kami membutuhkan kalian! Aku sangat kesepian tanpa kalian! Kenapa kalian
biarkan aku kesepian!”
Aku tak bisa
menahan diriku lagi. Segera kudekap adikku dari belakang. Air mataku akhirnya
jatuh juga. Timothy berbalik lalu memelukku erat, sangat erat. Ia tenggelam
dalam pelukanku dan tangisannya.
“Kenapa mereka
tega melakukan ini pada kita! Kenapa! Apa mereka tak tahu betapa kita
merindukan mereka!” isak Timothy.
“Aku tahu, tapi
aku tak bisa berbuat apapun. Tuhan telah menakdirkan ini semua,” ujarku.
“Tapi apa salah
kita! Apa dosa kita! Kenapa kita ditakdirkan seperti ini?”
“Jangan bicara
seperti itu,”
“Apa Tuhan
membenci kita? Kenapa Tuhan mengambil ayah dan ibu secepat ini?”
“Tidak, Timmy.
Tuhan menyayangi kita,”
“Tapi kenapa, Koh! Kenapa ini terjadi,”
“Timmy... Kumohon
jangan seperti ini...”
Adikku terisak
semakin hebat. Aku mencoba menenangkannya tetapi aku sendiri sudah kalap dengan
tangisanku. Aku mencoba menegarkan diriku, lalu berlutut sampai tubuhku
setinggi tubuh adikku.
“Timmy, inilah
hidup. Kita tak akan tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Kita mungkin
mengalami hal-hal buruk, tapi percayalah akan selalu ada hikmah dari semua
kejadian,” ujarku.
“Apa Tuhan sedang
menghukum kita?” tanyanya. Aku menggeleng.
“Tidak. Tuhan
lebih menyayangi ayah dan ibu daripada kita menyayangi mereka,”
“Tapi... Koh, aku merindukan ayah dan ibu. Aku
sangat merindukan mereka,”
“Aku juga
merindukan mereka, Timmy. Aku sangat merindukan mereka. Sekarang setelah mereka
pergi, hanya kau yang kumiliki. Kau juga, kau tak boleh meninggalkanku,”
Timothy memelukku
lagi.
“Maafkan aku, Koh. Maafkan aku karena aku tak mau
bicara padamu selama ini. Maafkan aku karena aku sempat membencimu. Aku sadar,
hanya kau yang kumiliki sekarang setelah ayah dan ibu pergi,” ujarnya
terbata-bata.
“Kau jangan
membenciku lagi. Aku tak pernah membencimu. Terkadang kau mengesalkan dan
membuatku marah, tapi aku tak pernah membencimu. Aku sangat sayang padamu
karena kau satu-satunya yang ayah dan ibu titipkan padaku. Aku tak peduli
dengan uang atau barang-barang yang diwariskan mereka untukku. Aku rela itu
semua menjadi milikmu, asalkan aku memilikimu. Itu saja,”
“Kau juga, jangan
marah padaku karena aku pernah membencimu,”
“Tidak. Tidak
akan,”
“Aku akan
melakukan apapun agar kau tak menaruh dendam padaku,”
“Benarkah?”
“Aku
sungguh-sungguh,”
Aku terdiam
sejenak.
“Timmy, maukah kau
melakukan sesuatu untukku?”
“Aku akan berusaha
melakukan apapun yang kau mau,”
“Setelah ini, kumohon
kau mulailah berbicara. Aku merindukan suaramu. Aku sedih melihatmu terkadang
menjadi bahan olok-olok orang lain. Kau mau ‘kan mulai bicara lagi?”
Timothy terdiam.
Ia menatapku dalam.
“Asalkan kau tak
menaruh dendam padaku, tak akan membenciku, dan tak akan pernah berusaha
melompat lagi dari Esplanade bridge,”
ujarnya. Aku mengangguk.
“Bagaimana kau
tahu aku pernah hampir melompat?” tanyaku.
“Jiejie yang
menceritakan semuanya. Kumohon jangan pernah terfikir untuk melompat dari
jembatan itu lagi,” jawabnya.
Aku tersenyum
kecil.
“Jika aku melompat
dari atap, bagaimana?” godaku.
“Aku tak mau
bicara lagi,” jawabnya.
“Jika aku melompat
dari tempat tidur?”
“Silahkan. Lakukan
saja,”
“Hmm... Atau jika
aku melompat dari atas meja makan, kau masih akan bicara padaku?”
“Aku tak mau
mengakuimu sebagai kakakku,”
“Kenapa?”
“Karena Leonard
Yeo tak akan melakukan hal konyol seperti itu,”
“Tapi jika aku
melakukan itu, bagaimana?”
“Oh, kau pasti
kerasukan arwah yang lain. Aku akan memanggil orang yang mampu mengusir roh
jahat,”
Aku menatap
Timothy, lalu kami tertawa bersama. Kulirik Tiffany yang menonton kami dari
jauh. Ia lalu berjalan ke arah kami.
“Kalian sudah
berbaikan?” tanya Tiffany.
“Sudah. Timothy
bahkan sudah mau bicara sekarang,” jawabku.
“Bagaimana jika
aku tak mau bicara?” tanya Timothy.
“Hey, seperti
itukah suaramu? Kau punya suara yang bagus, Timmy!” puji Tiffany.
“Benarkah? Tapi...
Aku malu jika aku bersuara lagi. Maksudku, orang-orang lain... Mereka...”
“Mereka akan
terkejut mendengarmu bicara,” potongku.
“Jika mereka
berfikir bahwa selama ini aku berbohong, bagaimana?”
“Bukankah kau
telah menjelaskan pada mereka yang sebenarnya sejak awal?”
“Memang. Hanya
saja... Kurasa aku tak mau menjadi orang yang banyak bicara,”
“Tak apa-apa. Kau
sudah mulai berbicara pun aku sudah senang,”
“Kemarin kau
sempat menghinaku karena aku tak mau bicara. Kau bilang aku ini bisu,”
“Aku tak
menghinamu. Aku hanya menyindirmu, mencoba mencari cara agar kau mau bicara.
Buktinya sekarang kau mau bicara, ‘kan?”
Timothy tersenyum
kecil.
“Lee, kapan kita
akan kembali?” tanya Tiffany.
“Entahlah,”
jawabku, “Aku tiba-tiba merasa nyaman berada disini,”
“Lagipula sudah
lama aku tak bermain di pantai. Jiejie,
selagi kita berada di pantai kenapa tak kita nikmati saja? Maksudku, kau pernah
berkejaran di pantai ‘kan?” sambung Timothy.
“Maksudmu seperti
ini?”
Tiffany tiba-tiba
menyerang kami dengan cipratan air laut. Aku dan adikku kontan terkejut. Adikku
yang sudah lebih sigap ikut menyerangku dengan cipratan air. Kurasa perang air
telah dimulai. Kedua tanganku kugerakkan dengan cepat untuk menyerang balik
mereka. Gelak tawa menambah keasyikan perang air di sore hari yang cerah ini.
Aku bahagia bisa menikmati momen-momen berharga bersama dua orang yang kusayangi
sore ini. Tapi yang lebih membahagiakan adalah, bisa berbaikan dengan adikku
dan mengetahui bahwa ia akan mulai berbicara lagi. Tuhan, terima kasih.
----